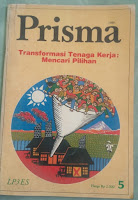Sumatera Utara: Contoh Paradoks Itu
Oleh Tika Noorjaya
RESENSI BUKU:
Judul Buku: The North Sumatran Regional Economy, Growth
with Unbalanced Development.
Penulis: Colin
Barlow dan Thee Kian Wie.
Penerbit: Institute
of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 1988.
Tebal: (xi +
98 halaman).
SEBAGAIMANA dikatakan
Prof. Mubyarto, masalah perekonomian daerah tampaknya bukan hanya belum kita
pelajari secara mendalam dan sungguh-sungguh, tetapi juga kebanyakan data
statistik yang diterbitkan BPS dan kantor-kantor cabangnya di daerah serta
BAPPEDA, belum mampu menerangkan berbagai paradoks sosial ekonomi yang tampak (BIES, April 1987). Padahal, mengkaji
masalah perekonomian daerah agaknya bukan hanya bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkaitan dengan daerah yang dikaji, tetapi juga dapat merupakan
pembanding bagi daerah lain, terutama daerah yang karakteristiknya mirip.
Penguasaan permasalahan daerah ini akan memungkinkan perbaikan dalam
perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya akan mampu
meyakinkan Pusat.
Demikianlah, buku yang memusatkan perhatian pada ketimpangan
pertumbuhan di Sumatera Utara ini agaknya tidak hanya patut menjadi perhatian Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan pihak-pihak terkait dengannya,
termasuk Pusat, tetapi juga provinsi-provinsi lain yang memiliki kecenderungan
serupa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Di manakah letak
ketimpangannya? Apakah penyebabnya? Dan, lebih penting lagi, kalau mungkin,
bagaimana upaya untuk menanggulanginya? Dalam kaitan inilah kehadiran buku The North Sumatran Regional Economy
cukup bermakna.
***
Selama ini, kita mengenal Sumut sebagai provinsi yang
demikian potensial, dengan kekayaan sumberdaya alamdan sumberdaya manusiany.
Posisi geografisnya memungkinkan keterkaitan secara luas baik dengan pusat
pasar dalam negeri maupun dengan pasar internasional. Latar belakang sejarahnya,
yang sudah lebih awal ditangani secara intensif – terutama dalam bidang
perkebunan yang berorientasi ekspor – juga semakin memantapkan provinsi ini
sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di luar Jawa.
Dari berbagai kondisi plus
ini, tidak mengherankan kalau sejak tahun 1970-an perekonomiannya telah tumbuh
demikian cepat dan telah mengantarnya sebagai salah satu provinsi yang
peetumbuhan produk domestik rata-rata tahuanannya tertinggi di Indonesia (hal.
1), dengan rata-rata pertumbuhan 7,9% per tahun selama periode 1974-1984 (hal.
9). Memang, karena melemahnya pasaran minyak bumi dan harga-harga berbagai mata
dagangan yang banyak dihasilkan provinsi ini – seperti karet, minyak sawit dan
aluminium – sejak tahun 1982 pertumbuhannya mengalami penurunan; tetapi kalau
kita simak perjalanan selama empat tahun Pelita IV, pertumbuhan ekonomi Sumut
mencapai 5,6%, jauh di atas tingkat rata-rata nasional yang hanya mencapai 3,7%
(Suara Karya, 29 Desember 1987). Dan,
seperti kebanyakan provinsi lain, penyumbang terbesar terhadap produk domestik
Sumut adalah sektor pertanian, sekalipun peranannya menurun dari 41,0% pada
tahun 1975 menjadi 37,7% pada tahun 1984 (hal. 8).
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang demikian baik, pada
dirinya mengandung ketimpangan yang serius dalam berbagai aspek, di mana
terjadi kontras antara sektor moderen yang maju dengan perkembangan yang baik
dibanding keragaan produsen tradisional yang perkembangannya semakin seret. Terutama dalam bidang pertanian,
gejala dualisme yang diwariskan sejarah, dengan pembagian yang kontras antar
segmen-segmen masyarakat – seperti yang telah dikaji oleh Boeke (1953) –
ternyata tidak menunjukkan perubahan (hal. 4). Demikian pula halnya dengan
ketimpangan antar subsektor dalam sektor manufaktur, sekalipun tidak semenonjol
dalam bidang pertanian.
Dualisme dalam pertanian, misalnya, dapat ditunjukkan dengan
perbandingan kembalian kotor (gross
return) yang mencapai Rp 3,54 juta per
pekerja bagi karyawan perkebunan besar, sedangkan petani perkebunan rakyat
(dalam hal ini karet, kelapa, kopi, dan cengkeh) hanya mendapat Rp 0,47 juta per keluarga (hal. 43); suatu
perbandingan yang sungguh terpaut jauh kalau angka terakhir ini dikonversi
dengan jumlah orang dalam keluarga pekebun (smallholders)
dimaksud, sekaipun untuk yang terakhir ini mungkin saja ada hasil dari usaha
lain yang dalam analisanya tidak ikut
dibahas. Untuk beberapa budidaya, tentu saja ketimpangan ini dapat dijelaskan
dengan rendahnya produktivitas dan sempitnya pemilikan lahan, di samping
kurangnya akses petani kecil terhadap berbagai input (terutama modal),
informasi, dan kurang menguntungkannya struktur tataniaga hasil budidayanya,
karena jauhnya transportasi serta kurang baiknya prasarana (misalnya bagi
petani kecil karet di wilayah pantai timur).
Di lain pihak, dualisme dalam sektor manufaktur, misalnya,
dapat ditunjukkan dengan nilai tambah per tenaga kerja yang mencapai Rp 9,02
juta untuk sektor moderen, dan Rp 299 ribu untuk sektor tradisional. Lagi-lagi
perbandingan yang mencolok. Kalau informasi ini dibandingkan dengan data sensus
industri nasional tahun 1974/1975, yang merupakan survey lengkap terhadap semua
subsektor industri, tampaklah bahwa dualisme di Sumut lebih nyata dibanding
Indonesia secara keseluruhan.
Dalam kaitan dengan keunggulan sektor moderen ini (baik
dalam bidang pertanian maupun manufaktur), menarik untuk menyimak peringatan
pengarang bahwa sektor moderen di Sumatera Utara mempunyai masalah internalnya
sendiri ... yaitu rendahnya efisiensi pada kebanyakan perusahaan, terutama bila
dibandingkan dengan usaha yang sama di luar negeri (hal. 5).
Ketimpangan lainnya adalah sehubungan dengan pembagian
wilayah, di mana dataran sebelah timur yang subur dan mempunyai potensi alam
yang lebih banyak, berkembang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan wilayah
bagian barat dan wilayah pegunungan. Dalam hal produk domestik tahun 1982
(dengan harga konstan), misalnya, sementara wilayah pantai barat mencapai Rp
247 ribu/kapita dan wilayah pegunungan mencapai Rp 276 ribu/kapita, maka
wilayah pantai timur bagian selatan mencapai Rp 309 ribu/kapita dan wilayah
pantai timur bagian utara mencapai Rp 349 ribu/kapita (hal. 22). Sebagai
tambahan terhadap keragaan ini, adalah sangat substansialnya perbedaan
pendapatan per kapita antara wilayah kerja kabupaten dengan kotamadya, di mana
yang disebut belakangan cenderung mempunyai produk domestik yang lebih tinggi
dibanding yang disebut pertama, dengan perbandingan yang bahkan dapat mencapai
dua kali lipat (kecuali bagi Kotamadya Sibolga yang di bawah rata-rata produk
domestik per kapita wilayah pantai barat).
Lagi pula, walapun pemerintah telah berupaya untuk
memperbaiki jalan-jalan serta berbagai prasarana lainnya, namun sebagian besar
pengeluaran tersebut menguntungkan wilayah sekitar Medan, tempat berlokasinya
sebagian besar sektor moderen. Di sisi lain, investasi yang sangat mahal di
Sumut – proyek hydroelektrik raksasa Asahan dan Inalum (PT Indonesia Asahan
Aluminium) yang nilai investasinya mencapai 411 milyar yen misalnya, juga
merupakan unit ekonomi enclave, yang
pengaruhnya terhadap perekonomian setempat kecil sekali.
***
Tentu saja, Pemda Sumut dan Pemerintah Pusat telah melakukan
berbagai upaya untuk mengurangi berbagai ketimpangan yang ada, antara lain
ditunjukkan dengan meningkatnya perbaikan prasarana, seperti sekolah, jalan,
pembangkit tenaga listrik, moderenisasi pelabuhan dan lain-lain, yang telah
meningkatkan potensi dan daya saing provinsi ini, sekalipun masih tetap perlu
ada upaya untuk lebih memperbaiki prasarana, terutama jalan di luar wilayah pantai
timur (hal. 83). Saran klasik, yang telah diungkapkan A. T. Mosher lebih du
dasawarsa yang lalu ketika membahas lima faktor mutlak dalam pembangunan
pertanian.
Keberhasilan program BIMASdan INMAS telah mengurangi
(fragmentasi) pasar. Demikian juga pembangunan proyek Perusahaan Inti Rakyat
Perkebunan (PIRBUN) antara lain juga dimaksudkan pada arah penyeimbangan dan
mengubah pola dualisme, sekalipun hanya meliput sebagian kecil penduduk saja
dan tidak besar pengaruhnya dalam mengubah kendala utama, yang karenanya
pengarang menyarankan untuk lebih memperluas pasokan kredit dan informasi
seperti halnya yang terjadi di Muangthai untuk program yang sama (hal. 86).
Sementara itu, kegiatan yang lebih mengarah pada upaya
penyeimbangan wilayah seperti halnya operasi khusus terpadu Maduma telah pula menampakkan hasilnya,
terutama dalam menggugah etos kerja dan komitmen pembangunan pada masyarakat
desa di kelima kabupaten yang dicakup dalam program ini, yang empat di
antaranya tak lain adalah wilayah pantai barat Sumut yang, konon, dahulu
merupakan “peta kemiskinan”.
***
Itu semua hanya sebagai contoh dari berbagai upaya dalam menanggapi permasalahan
ketimpangan pertumbuhan yang dialami Sumut.
Namun perlu juga diingat, seperti diungkapkan pengarang,
masalah pertumbuhan sama sekali bukan hal yang unik, dan fenomena ketimpangan
perkembangan dapat dilihat sebagai karakteristik kebanyakan provinsi di
Indonesia, juga dalam perekonomian negara berkembang lainnya (hal. 87). Dalam
buku ini, memang, pernyataan di atas tidak diikuti dengan rincian lebih lanjut,
provinsi mana saja yang dimaksud; tetapi dalam hal ini kita dapat merujuk
kembali penyataan Mubyarto (BIES,
April 1987). Dikatakannya bahwa salah satu gambaran umum yang sangat menarik
dari survey perekonomian daerah adalah banyaknya “paradoks” dalam pembangunan
daerah, terutama yang tersaji dalam laporan dari Jawa Barat, Jawa Tengah
(termasuk DI Yogyakarta), Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Meskipun
laporan dari wilayah lain tidak secara eksplisit menyajikannya, namun cerita
tentang paradoks yang sama juga ditemukan. Uraian ini dialnjutkan dengan
pertanyaan manis: Apakah hal ini juga tidak berlaku bagi negara secara
keseluruhan? Tak pelak, suatu pertanyaan yang menarik kalau diingat betapa
sejak Pelita III komitmen nasional demikian gencar menekankan aspek pemerataan
dalam trilogi pembangunan kita.
Kalau paradoks pembangunan yang tercermin dari contoh Sumut
serta yang didukung oleh pengamatan Mubyarto ini ditarik “ke atas”, seyogyanya
ada pengkajian ulang untuk merumuskan kembali hakikat pembangunan itu sendiri.
Kalau pada tahun 1970-an banyak cerdik pandai yang mempermasalahkan merentannya
kemiskinan dan terabaikannya pemerataan dalam hubungan dengan perekonomian yang
sedang tumbuh pada waktu itu, maka sekarang pun tampaknya issue paradoks tersebut masih relevan untuk dikemukakan – sekalipun
pertumbuhan ekonomi tidak secemerlang dasawarsa 1970-an. Agaknya dapat kita
sepakati bahwa pembangunan tidak cukup hanya sekadar menjawab pertanyaan “untuk
apa”, tetapi juga “bagi siapa”. Bahkan David Korten (1988) dengan tegas
menyatakan bahwa pembangunan dengan pendekatan yang berorientasi kepada
masyarakat (people oriented) pun
perlu diubah menjadi pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development). Tentu
saja, itu semua jangan sampai menjadi
sekadar permainan kata-kata atau slogan politik, karena yang paling penting
adalah realitanya.
Kurang jelas, apakah penerbitan buku yang menarik ini akan
mampu mengundang para ilmuwan kita untuk mengkaji wilayah lainnya sertamenjawab
pertanyaan Mubyarto seperti yang telah dikutip di atas. Sebagai peminat yang
tidak dilahirkan di Sumut dan belum pernah berkunjung ke sana, ketertarikan
saya pada buku ini, misalnya, bukanlah karena judul besarnya, melainkan karena
judul kecilnya yang merangsang: sekalipun setelah selesai membaca buku ini
serta merta terungkap refleksi: Barangkali provinsi tempat saya dilahirkan juga
begitu. Kalau anda membaca buku ini, saya kira anda juga akan merasakannya.
TIKA NOORJAYA*
* Penulis adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Borobudur,
Jakarta.
Resensi
buku ini dimuat dalam Majalah Prisma 5, 1989, halaman
95-96.