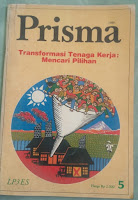Kelapa vs Kelapa
Sawit: Melerai Persaingan Antarsaudara
Oleh Tika Noorjaya
BELUM lama ini diberitakan produsen
kelapa/kopra mengeluh karena rendahnya harga yang mereka terima, seperti
laporan yang disampaikan kepada Menteri Muda UPPTK, Ir. Hasjrul Harahap ketika
berkunjung ke Buleleng (Bali) akhir Oktober lalu.
Karena itu, diperlukan upaya untuk
menanggulangi efek negatif persaingan antara kelapa (Cocos mucifera) dan kelapa sawit (Elaestica guinensis).
Dari
sekian banyak tumbuhan yang tersebar di negeri ini, rasanya tidak ada tumbuhan
lain selain kelapa yang setiap komponennya tanpa kecuali dapat dimanfaatkan.
Pucuk
daunnya yang disebut janur kuning, dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi
pesta-pesta. Daunnya yang sedikit tua dapat digunakan sebagai pembungkus
ketupat yang menambah semaraknya suasana lebaran. Lepas dari daunnya, lidi
dapat disusun menjadi sapu atau dipotong menjadi tusuk sate atau tusuk daun.
Ketika
pohon telah berbunga, dari batang bunga dapat dideres (dihisap) airnya untuk
dimasak menjadi gula jawa, sedangkan dari bunganya sendiri (manggar)
dapat diolah menjadi bahan gudeg.
Kelapa
muda yang disebut cengkir, dahulu digunakan untuk bahan sesaji dalam upacara adat
tertentu. Air kelapa muda? Siapa yang belum pernah merasakan nikmatnya ketika
diminum pada siang hari yang panas. Buahnya? Tentu saja, bahkan lebih banyak
lagi manfaatnya. Selagi muda, dagingnya dapat dimakan mentah, misalnya sebagai
campuran air bersih menjadi air santan sebagai bumbu masak yang lezat. Parutan
kelapa dapat juga dibuat serundeng, galendo atau campuran
penganan lain. Bahkan, daging buah kelapa tua dapat diolah menjadi minyak kelapa,
untuk menggoreng, dan sebagainya. Kalau tidak, dapat juga dikeringkan
sebagai kopra, agar tahan lama.
Di luar
daging, ada tempurung dan sabut. Tempurung dapat dibuat menjadi alat minum,
gayung, bahan hiasan, kancing dan sebagainya, bahkan alat bunyi bagi tarian
Minangkabau. Arangnya mempunyai kalori yang tinggi, di samping dapat
bertahan lama karena kerasnya. Sabutnya dapat dibuat alat-alat rumah tangga
seperti kesed, sapu, tali dan sebagainya.
Batang pohonnya yang panjang dan lurus serta kuat, antara
lain dapat digunakan sebagai jembatan atau saluran air.
Tampaknya tidak berlebihan andaikata kelapa disebut
budidaya multiguna. Tetapi mengapa tidak primadona?
Kelapa Sawit: Primadona
Bebarapa tahun lalu, kelapa sawit telah lebih dahulu diproklamasikan sebagai
primadona sektor pertanian, khususnya sub-sektor perkebunan, dengan berbagai
alasan. Rendahnya biaya produksi, kesempatan kerja; prospek pemasaran, dan
sebagainya. Sehingga, dengan baiknya posisi kelapa sawit pada masa lalu maka
budidaya ini telah dipacu sedemikian rupa dalam bentuk perluasan tanaman yang
melibatkan PNP/PTP, perkebunan swasta dan petani/rakyat. Akibatnya, jatuhnya
harga minyak sawit beberapa bulan yang lalu, tak pelak lagi ”memukul” mereka.
Tetapi, barangkali seperti primadona sungguhan; banyak
tingkahnya yang aneh-aneh. Seperti kita ketahui, harga jual minyak sawit
dibedakan antara harga jual lokal dan harga ekspor (terakhir, harga jual lokal
adalah Rp 425,-/kg). Ketika harga ekspor lebih tinggi daripada harga jual
lokal, konon terjadi ”kucing-kucingan”, dan diantara ”kucing-kucing” tersebut
ada yang berhasil mengekspor minyak sawit jatah pasar lokal.
Beberapa bulan lalu, ketika harga ekspor lebih rendah
dibanding kelapa sawit, konon pula ada ”kucing” yang memanfaatkan jatah ekspor
untuk dipasarkan lokal, sehingga ”membanjiri” pasar lokal dan menekan harga
kelapa. Padahal, alasan penetapan harga jual lokal cukup kuat, yaitu melindungi
petani kelapa agar tetap bergairah menghasilkan kelapa.
Kebijakan ini tampaknya wajar, karena kita ketahui pula
bahwa luas areal kelapa dalam sub-sektor perkebunan menempati peringkat
pertama, yang kiranya dapat diartikan sebagai banyaknya orang yang
berkepentingan dengan tanaman ini, apalagi kalau diingat bahwa berdasarkan data
tahun 1985, lebih dari 98% areal tanaman kelapa adalah kelapa rakyat, yang
mungkin pemiliknya menggantungkan sebagian hidupnya dari tanaman ini.
Memang, antara kelapa dan kelapa sawit terdapat hubungan
saudara yang cukup erat. Selain sama-sama keluarga palma, keduanya merupakan penghasil minyak nabati di samping bunga matahari, kedele, minyak zaitun
dan beberapa jenis lainnya, yang dalam beberapa hal dapat saling menggantikan.
Satu hal yang membedakannya adalah biaya produksi minyak sawit yang lebih
rendah daripada minyak kelapa, sehingga persaingannya di pasar cenderung memukul (petani) kelapa.
Namun, seperti dipaparkan di muka, fungsi sosial kelapa
lebih menonjol daripada kelapa sawit, sehingga cukup alasan andaikata ada
perlakuan khusus (persus) bagi para
petani kelapa; apalagi kalau diingat beberapa waktu yang lalu petani kelapa
pernah dibebani pungutan-pungutan tertentu; pernah ada Cess Kopra; Dana
Rehabilitasi Kopra, dan sebagainya.
Perlakuan Khusus
Mari kita melihat permasalahan kelapa secara umum, yakni konsumsi yang
terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatnya konsumsi
per kapita; tanpa diimbangi peningkatan produksi.
Menurut Sensus Sosial Ekonomi Nasional tahun 1976,
konsumsi kelapa per kapita per tahun mencapai 11,12 kg setara kopra. Tetapi,
data ini belum mempertimbangkan konsumsi kelapa segar sebagai kelapa muda,
sehingga konsumsi sebesar 11,12 kg per kapita per tahun tampaknya terlalu
rendah, dan dengan meningkatnya taraf kemakmuran maka konsumsi kelapa sekarang
diperkirakan mencapai 14-16 kg setara kopra per kapita per tahun.
Peningkatan konsumsi ini antara lain tercermin dengan
meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam
negeri, di mana kalau pada tahun 1978 minyak goreng yang berasal dari minyak
sawit baru 100 ribu ton, pada awal tahun 1984 sudah mencapai 750 ribu ton;
meski waktu itu harga minyak sawit di pasar internasional sangat baik.
Memang, kebijakan pengalokasian sebagian minyak sawit
untuk konsumsi minyak goreng dalam negeri ini telah dapat ”menolong” konsumen
di dalam negeri, tetapi itu berarti menekan petani kelapa dan melepas pangsa
pasar (market share) minyak sawit di
pasar internasional, yang dengan sigap dimanfaatkan, terutama oleh negara
tetangga kita, Malaysia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia
(padahal menurut sejarahnya, kelapa sawit Malaysia berasal dari Indonesia).
Lain lagi dengan permasalahan rendahnya produktivitas.
Keragaan yang kurang menggembirakan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama;
banyaknya tanaman tua, yang berdasarkan data tahun 1985 dengan luas areal
3.059.710 hektar, 27,2% diantaranya merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM),
6,8% tanaman tua/rusak (berumur lebih
dari 60 tahun) dan sisanya (66,0%) merupakan Tanaman Menghasilkan (TM).
Tetapi, dari areal TM tersebut sekitar 40% diantaranya berumur lebih dari 50 tahun.
Kedua, terlambatnya
peremajaan bagi tanaman tua/rusak dan tanaman yang berumur lebih dari 50 tahun
(lihat penjelasan pertama), karena (terutama) peremajaan perkebunan rakyat
mengalami berbagai hambatan antara lain kesukaran memperoleh bibit, pengadaan
pupuk dan sarana produksi lain, disamping kurangnya kemampuan dan kemauan
petani.
Ketiga, seringnya
terserang hama/penyakit tanaman serta adanya musim kering, seperti halnya pada
tahun 1982-1983 di mana menyebabkan turunnya produksi secara drastis. (Mengenai
musim kering ini, tampaknya perlu ada perhatian khusus, sehubungan dengan
ramalan beberapa pakar yang mengingatkan kemungkinan terjadinya siklus musim
lima-tahunan yang berarti diramalkan akan terjadi musim kering pada tahun
1987-1988).
Keempat, masalah
pemasaran yang meliputi harga kopra yang kurang merangsang petani untuk
berproduksi dan rantai pemasaran yang panjang, termasuk kurang terjaminnya
pengangkutan antarpulau. Padahal, seperti kita maklumi, meskipun tanaman kelapa
hampir tersebar di seluruh Indonesia, hanya beberapa daerah saja yang potensi
kelapa dan kopranya cukup besar, antara lain Sulawesi, Maluku, Riau dan
beberapa pulau lainnya; sedangkan daerah konsumen terbesar berada di Pulau Jawa.
Salah satu akibat dari rendahnya produktivitas adalah
tingginya biaya produksi per satuan hasil. Sedangkan apabila digabungkan dengan
masalah peningkatan konsumsi per kapita per tahun dapat menyebabkan kelebihan
permintaan, yang secara teoritis dapat mengangkat harga. Tetapi, karena
komoditi ini dapat digantikan dengan bahan minyak nabati lain (termasuk minyak
sawit) yang biaya produksinya lebih rendah, maka di pasar kelapa kurang dapat
bersaing.
Karena itulah, diperlukan perlakuan khusus untuk merangsang
petani kelapa agar bergairah untuk berproduksi, dengan meningkatkan
produktivitas dan mutunya. Upaya tersebut dapat berupa perangsang harga maupun
perangsang bukan harga, agar mampu menjawab secara positif permasalahan seperti
dipaparkan di muka.
Untuk itu, pengaitan kelapa dengan kelapa sawit yang
cenderung merugikan petani-petani kiranya perlu ditinjau kembali, antara lain
dengan mempertajam pasar bagi masing-masing, sehingga tidak lagi terjadi
”persaingan” antara keduanya. Kelapa dengan fungsi sosial yang lebih besar
lebih diarahkan untuk memenuhi konsumsi
dalam negeri dengan melakukan upaya lanjutan, antara lain peningkatan
produktivitas, efisiensi serta penataan distribusi pemasarannya, sehingga
konsumen dapat membeli dengan harga yang wajar, sementara para petani kelapa
tidak dirugikan.
Sedangkan minyak sawit, baik dalam bentuk CPO (Crude
Palm Oil) maupun dalam bentuk produksi industri hilir, diarahkan pada
pasar luar negeri, dengan upaya lanjutan antara lain perlunya peningkatan daya
saing dengan menurunkan harga pokok maupun perbaikan mutu, termasuk penataan
administrasi ekspor agar memudahkan proses pengeksporan itu sendiri. Upaya
terakhir ini, tampaknya sekarang memperoleh peluang, karena konon Malaysia
mengurangi ekspor CPO dan mengarahkannya menjadi produk lanjutan; dengan
demikian kekosongan pasar CPO yang ditinggalkan Malaysia dapat kita ”isi”.
Sementara itu, dengan membaiknya harga CPO akhir-akhir
ini di pasar internasional (pada akhir Oktober 1986 mencapai 340 dollar AS
metrik ton), kiranya tidak terjadi lagi main ”kucing-kucingan” yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Selain itu, ketahanan masing-masing komoditi terhadap
gejolak perekonomian dunia tampaknya perlu terus dimantapkan, apalagi kalau
benar ramalan yang berkembang belakangan ini, bahwa harga-harga komoditi primer
seperti CPO tidak akan banyak bergerak dari tingkat yang sekarang.
Artikel ini dimuat di Harian Prioritas, 25 Februari
1987.