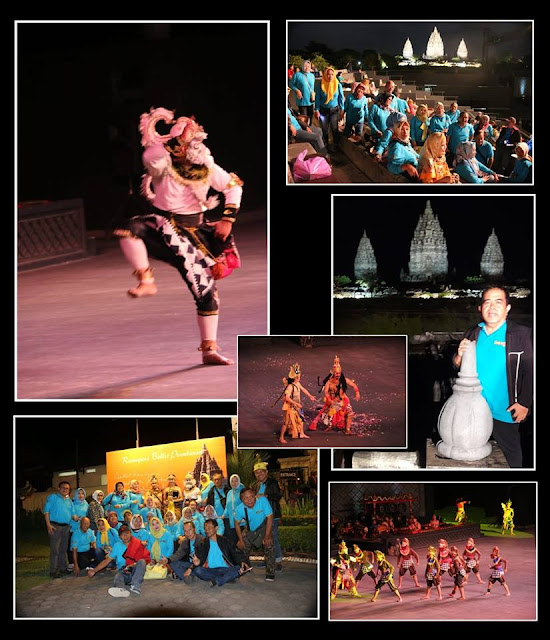ASEP SAEFUDDIN, Dari Perguruan Tinggi Bangun Negeri, Rajawali Press, Jakarta, Maret 2017, 242 halaman.
ISBN 978-602-425-145-1.
___
Penulis buku ini, Prof Dr. Ir. Asep Saefuddin, adalah anak saintifik Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion. Betapa tidak. Saya mengenal Kang Asep sejak sama-sama kuliah di Insitut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1976. Saya tahu bahwa sejak awal Kang Asep menjadi “anak emas” Pak Andi Hakim, antara lain karena merupakan sedikit dari mahasiswa IPB yang IPK-nya selalu tinggi.
Dari biografi singkat di bagian akhir buku ini (Bagian Delapan, halaman 194-240), segera tampak, bahwa perjalanan hidup, keilmuan dan karir Kang Asep banyak diwarnai dan tak lepas dari peran Pak Andi. Tak heran kalau dua tahun terakhir Kang Asep menjadi anggota Tim Pengusul Pemberian nama Jl. Prof. Dr. H. Andi Hakim Nasoetion, -- jalan menuju Kampus IPB Baranangsiang yang dulu disebut Jl. Rumah Sakit II.
Sekalipun berbeda latar belakang antara Batak dan Sunda, ada kesamaan antara Pak Andi dengan Kang Asep: Keduanya sama-sama Guru Besar IPB bergelar Prof Dr Ir, berkeahlian di bidang statistika, menjadi administartor perguruan tinggi, aktivis kampus, ... dan suka menulis dalam berbagai denominasi pemikiran.
Buku ini contohnya. Buku ini bukan buku ilmiah kepakaran Kang Asep sebagai ahli statistika, melainkan penuangan gagasannya yang terkait dengan pengalamannya menjadi administrator perguruan tinggi, tepatnya sebagai Rektor Universitas Trilogi sejak 3 Oktober 2013 hingga sekarang. Luar biasa, dalam rentang yang pendek itu, terkumpul 49 tulisan yang sebagian besar pernah dimuat di media massa. Karena Universitas Trilogi berpilarkan Teknopreneur, Kolaborasi, dan Kemandirian, maka salahsatu Bagian dari kumpulan tulisan ini fokus pada ketiga pilar tersebut.
Sebagai rampaian tulisan yang serba singkat, tak terhindarkan bahwa uraiannya tak sampai final untuk jadi sebuah proposal kegiatan yang rinci, tetapi sejumlah gagasannya kiranya akan menjadi tongkat penunjuk ke arah ketidaktahuan yang harus dielaborasi kemudian.
Buku ini dibagi menjadi tujuh Bagian, yang ketujuhnya diberi judul awal “Perguruan Tinggi”, baru diikuti dengan pokok bahasannya, yaitu: (1) Generasi Teknopreneur, (2) Ilmu Pengetahuan, (3) Etika dan Sosial Politik, (4) Gagasan dan Riset, (5) Kolaborasi dan Kemandirian, (6) Revolusi Mental dan Pendidikan, serta (7) Sistem Pendidikan Nasional.
Itulah garis besar gagasan Prof Dr Ir. Asep Saefuddin untuk membangun negeri dari perguruan tinggi. Peran yang menjadi obsesinya agar perguruan tinggi menjadi lumbung ide sebagai jalan penyelesaian masalah bangsa, ... sebagai tambahan khazanah urgensi perguruan tinggi.
Perguruan tinggi memang bukan segalanya, namun segalanya bisa lahir dan diselesaikan di sini. “Dari Perguruan Tinggi, Mari Kita Membangun Negeri”, katanya (halaman ix).